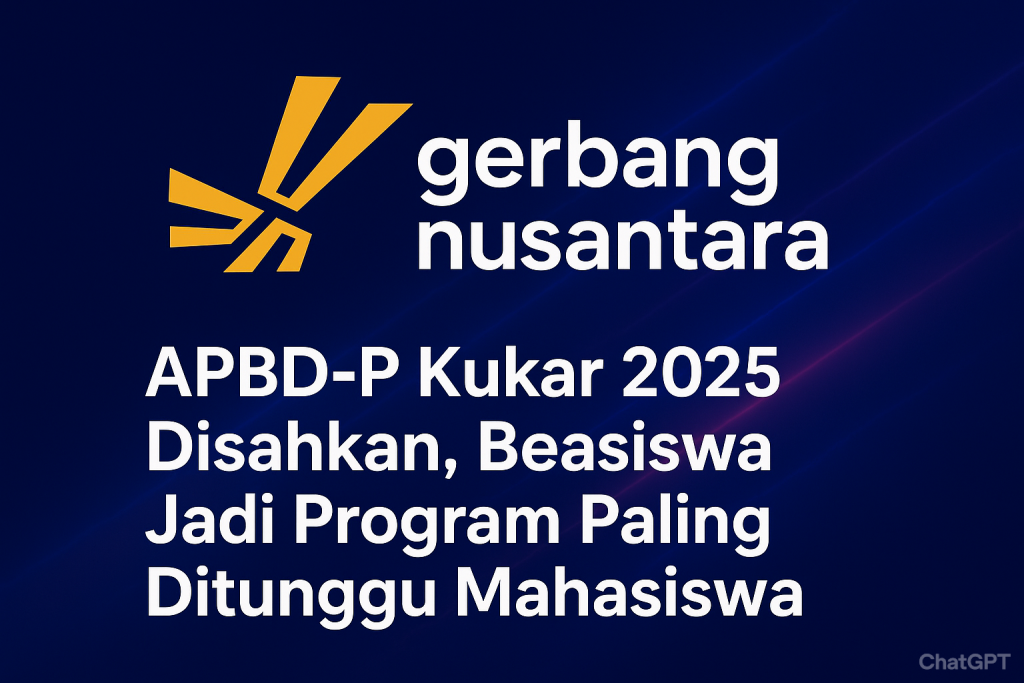Gerbang Nusantara menyoroti buku “Politik Elektoral: Dipilih Mayoritas Rakyat Kukar, Dibatalkan MK” terasa lebih sebagai pembenaran diri ketimbang refleksi demokrasi. Edi Damansyah seolah ingin meyakinkan publik bahwa dirinya adalah korban Mahkamah Konstitusi (MK), padahal fakta hukum justru berkata sebaliknya.
Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 sudah jelas sebelum pencalonan berlangsung: kepala daerah yang sudah menjabat dua periode penuh, meski tidak berturut-turut, tidak berhak lagi maju. Artinya, sejak awal Edi tahu bahwa jalannya terhalang. Namun, ia tetap memaksakan diri maju, mendorong partai pengusung, dan melibatkan banyak pihak untuk menghabiskan energi, waktu, serta uang negara demi proses yang akhirnya sia-sia.
Kerugian negara akibat pencalonan ini tidak kecil. Berdasarkan perhitungan anggaran, Pilkada Kukar 2024 menelan biaya sekitar Rp103,6 miliar. Anggaran sebesar itu seharusnya bisa diarahkan untuk pembangunan infrastruktur desa, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Namun sebagian besar terbuang percuma karena proses demokrasi harus diulang akibat ambisi politik seorang tokoh yang sejak awal sudah tidak memenuhi syarat.
Ironisnya, alih-alih bertanggung jawab atas kerugian rakyat, Edi justru menyalahkan MK. Padahal, MK hanya menjalankan konstitusi. Sikap menyalahkan lembaga hukum ini bukan saja tidak bijak, tetapi juga merusak pendidikan politik masyarakat. Bagaimana mungkin seorang pemimpin mengajarkan bahwa aturan bisa dinegosiasikan hanya karena merasa didukung suara mayoritas?
Demokrasi bukanlah panggung untuk membenarkan ambisi pribadi. Demokrasi adalah kombinasi antara suara rakyat dan kepatuhan hukum. Tanpa itu, demokrasi hanya menjadi alat untuk membungkus keserakahan politik.
Edi harusnya legowo menerima bahwa dirinya gagal bukan karena “dirampas MK”, melainkan karena melanggar aturan yang ia tahu sejak awal. Dan rakyat Kukar pun berhak menuntut pertanggungjawaban moral—karena ratusan miliar uang negara telah terbuang sia-sia demi pencalonan yang cacat hukum.