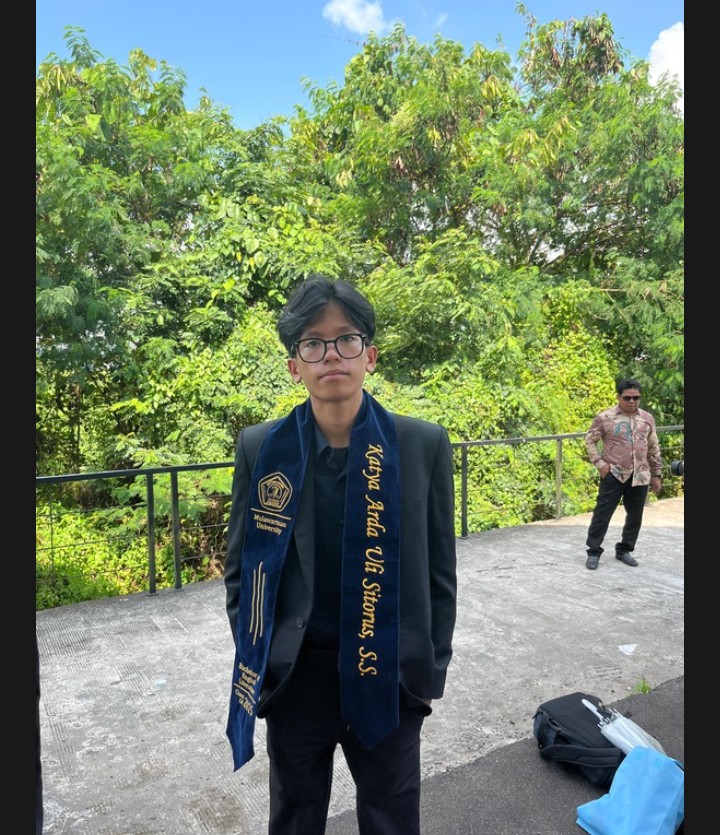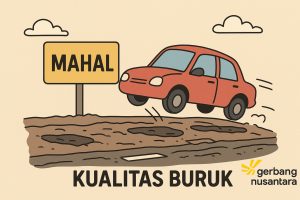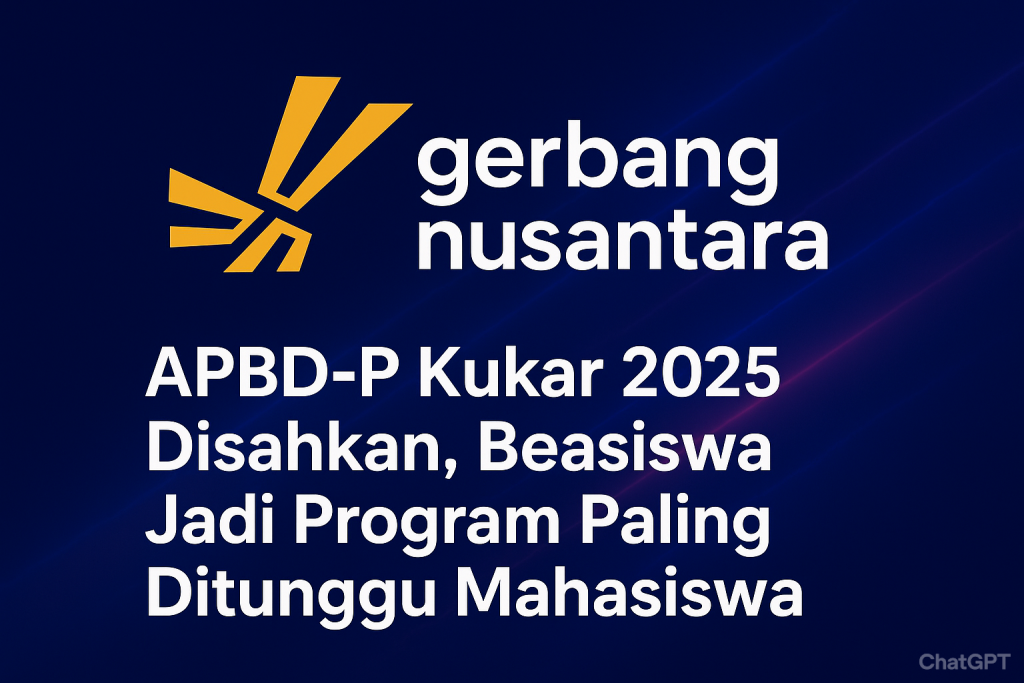Penulis: Mindo, Mahasiswa Universitas Mulawarman
Setiap kali pemerintah mengumumkan APBN, satu hal yang hampir selalu jadi sorotan adalah subsidi. Angkanya tidak kecil, bahkan bisa mencapai ratusan triliun rupiah, terutama untuk energi seperti BBM, listrik, dan gas. Kalau kita lihat sekilas, subsidi ini terdengar mulia—pemerintah berusaha meringankan beban rakyat, menjaga harga tetap terjangkau, dan memastikan stabilitas ekonomi. Tapi di balik itu, muncul pertanyaan besar: apakah subsidi benar-benar membantu rakyat kecil, atau justru jadi beban jangka panjang bagi keuangan negara?
Subsidi memang punya fungsi vital. Bayangkan kalau harga BBM atau listrik sepenuhnya diserahkan ke mekanisme pasar—sudah pasti harga melonjak dan banyak keluarga menengah ke bawah akan kesulitan. Dengan subsidi, setidaknya ada rasa aman bagi masyarakat karena kebutuhan dasar masih bisa dijangkau. Tidak hanya soal harga, subsidi juga punya efek politis. Pemerintah bisa menjaga stabilitas sosial, karena kita tahu, kenaikan BBM biasanya langsung memicu demonstrasi besar-besaran. Jadi dalam jangka pendek, subsidi sering dianggap ‘obat penenang’ yang membuat masyarakat tidak terlalu terbebani.
Namun, masalahnya muncul ketika kita bicara soal efektivitas dan keberlanjutan. Subsidi sering kali tidak tepat sasaran. Contoh sederhana: orang kaya yang pakai mobil pribadi juga ikut menikmati BBM bersubsidi, padahal mereka jelas tidak termasuk kelompok rentan. Akibatnya, alokasi subsidi yang seharusnya fokus membantu rakyat miskin malah ikut dinikmati oleh mereka yang sebenarnya tidak butuh. Inilah yang bikin sistem subsidi kita sering dianggap boros dan tidak efisien.
Lebih jauh, subsidi juga memakan porsi besar dalam APBN. Jika anggaran ratusan triliun tersedot untuk subsidi energi, ruang fiskal untuk hal-hal lain seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur jadi makin sempit. Padahal sektor-sektor itulah yang sebenarnya bisa mendorong pembangunan jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi ada trade-off besar di sini: apakah kita mau terus menyalurkan subsidi konsumtif, atau berani mengalihkan dana itu untuk investasi produktif?
Di sisi lain, pemerintah juga berada dalam posisi serba salah. Kalau subsidi dikurangi, harga BBM atau listrik naik. Efeknya langsung terasa di kantong masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Inflasi naik, harga sembako ikut melonjak, dan pada akhirnya bisa memicu keresahan sosial. Tetapi kalau subsidi terus dipertahankan, beban fiskal negara bisa semakin berat. Bahkan tidak menutup kemungkinan menimbulkan defisit anggaran yang makin melebar. Dilema inilah yang membuat isu subsidi selalu jadi topik panas, baik di ruang akademis, media, maupun jalanan.
Lalu, bagaimana seharusnya subsidi dikelola? Menurut saya, kuncinya ada pada ketepatan sasaran. Subsidi sebaiknya tidak diberikan secara menyeluruh, tetapi dialihkan dalam bentuk bantuan langsung yang berbasis data akurat, misalnya lewat integrasi NIK atau sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan begitu, hanya mereka yang benar-benar membutuhkan yang mendapatkan manfaat. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan edukasi publik bahwa subsidi bukanlah solusi permanen. Masyarakat harus paham bahwa subsidi hanyalah instrumen sementara, bukan jaminan selamanya.
Sebagai mahasiswa, kita juga perlu melihat isu ini dengan lebih kritis. Jangan hanya melihat subsidi sebagai ‘hak’ yang harus selalu diberikan, tapi pahami bahwa ada konsekuensi fiskal besar di baliknya. Uang negara itu terbatas, dan setiap rupiah yang masuk ke subsidi berarti ada sektor lain yang harus dikorbankan. Pertanyaannya, apakah kita mau terus terjebak dalam pola subsidi konsumtif, atau kita mulai berani mengarahkan anggaran untuk hal-hal yang lebih berjangka panjang?
Pada akhirnya, subsidi tidak bisa dilihat hitam-putih. Ia bukan semata-mata pro-rakyat atau anti-rakyat. Yang terpenting adalah bagaimana tata kelolanya dilakukan dengan transparan, akurat, dan berpihak pada kelompok yang paling rentan. Dengan begitu, subsidi bisa tetap menjadi jaring pengaman sosial, tanpa mengorbankan masa depan fiskal negara.