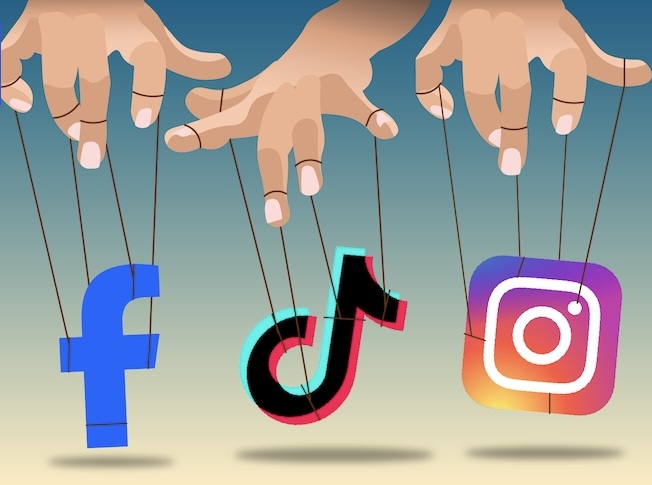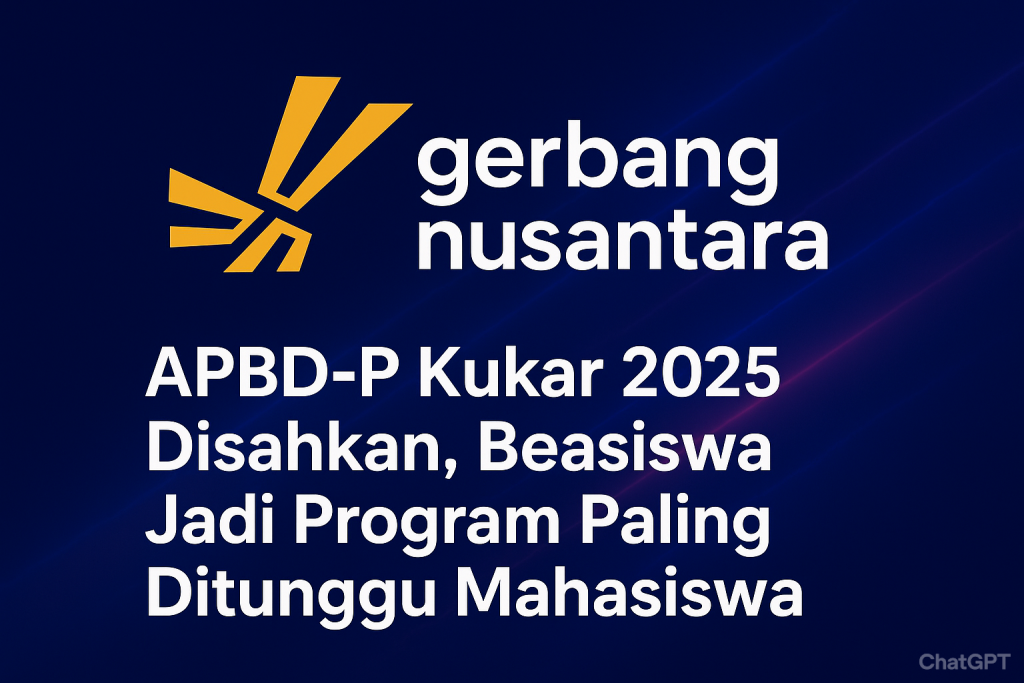Oleh: Filza Hayuning Wafa, Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta
Jakarta – Media jurnalistik Indonesia tengah menghadapi tantangan sekaligus peluang besar di era disrupsi digital. Transformasi teknologi melaju cepat, didorong penetrasi internet yang masif serta perkembangan kecerdasan buatan (AI). Pola konsumsi informasi masyarakat pun berubah drastis: berita tak lagi terbatas di koran atau televisi, melainkan berputar cepat di media sosial, berbalut teks singkat, visual atraktif, hingga video berdurasi detik.
Namun, derasnya arus digital juga membawa banjir informasi palsu. Hoaks, disinformasi, hingga manipulasi digital menjadi bagian dari ekosistem media hari ini. Survei Katadata Insight Center (2021) mencatat 30–60 persen pengguna internet di Indonesia terpapar hoaks, sementara hanya 21–36 persen yang mampu mengenalinya. Fakta ini menegaskan bahwa jurnalisme kini berada pada titik kritis: bukan hanya dituntut cepat, tetapi juga akurat dan kredibel.
Media Arus Utama dalam Tekanan Platform
Media arus utama seperti Kompas, Tempo, dan Tribun masih menjadi rujukan publik. Namun, dominasi mereka kian tergerus platform global seperti Google, Meta, dan TikTok yang menguasai distribusi berita sekaligus iklan digital. Laporan industri menunjukkan lebih dari 70 persen belanja iklan daring Indonesia justru mengalir ke platform asing.
“Media tidak bisa lagi bergantung pada iklan. Mereka harus mencari model bisnis baru: langganan digital, kolaborasi lintas platform, atau monetisasi lewat podcast dan video,” ujar Djony Herfan, Dosen Politeknik Negeri Jakarta.
Situasi semakin kompleks dengan maraknya hoaks politik menjelang Pemilu 2024. Data Tirto.id mengungkap mayoritas disinformasi tersebar dalam bentuk video pendek dan teks provokatif di media sosial. Format visual singkat ini kini menjadi medan pertempuran utama, di mana media profesional berhadapan langsung dengan arus hoaks yang bergerak cepat.
AI dan Jurnalisme Masa Depan
Kecerdasan buatan membuka peluang sekaligus ancaman baru. Di ruang redaksi, AI sudah digunakan untuk otomasi berita sederhana, analisis data, hingga personalisasi konten. Namun, risiko tetap besar, mulai dari konten fabrikasi, manipulasi gambar, hingga deepfake video.
“AI hanya bisa mengolah data. Tapi untuk menghadirkan jurnalisme yang kritis dan empatik, peran manusia tidak tergantikan,” tegas Alfons Yoshio, pemeriksa fakta Tirto.id.
Ke depan, AI diperkirakan banyak dipakai untuk memproduksi laporan rutin, sementara jurnalis manusia tetap dibutuhkan untuk reportase investigatif, liputan lapangan, serta penulisan dengan sensitivitas sosial.
Hoaks dan Pentingnya Verifikasi Fakta
Workshop Periksa Fakta Tirto (2025) menegaskan bahwa penyebar hoaks paham benar cara memanfaatkan emosi publik. Mereka kerap menggunakan foto lama, narasi provokatif, hingga video manipulatif. Survei Tirto dan Jakpat (2023) menunjukkan hampir 38 persen masyarakat pernah menyebarkan hoaks tanpa sadar.
Dalam kondisi ini, keterampilan verifikasi menjadi modal utama jurnalis. Alat seperti reverse image search, plugin InVID, hingga Wayback Machine banyak digunakan untuk melacak keaslian foto dan video. “Kemampuan cek fakta harus jadi bagian tak terpisahkan dari jurnalisme digital,” ujar Alfons Yoshio.
Jurnalisme Partisipatif dan Literasi Publik
Masyarakat kini tidak hanya sebagai konsumen informasi, tetapi juga produsen. Fenomena citizen journalism semakin marak, terutama dalam momen bencana alam, aksi protes, atau kejadian mendadak. Kehadiran jurnalis warga memperkaya ekosistem informasi, tetapi juga berisiko mempercepat penyebaran misinformasi ketika kontennya tidak diverifikasi.
Faktor psikologis turut memperkuat persoalan ini. Menurut American Psychological Association, orang cenderung membagikan informasi palsu ketika sesuai dengan identitas pribadi, norma sosial, atau ketika memicu emosi kuat seperti marah, simpati, atau takut. Akibatnya, hoaks lebih mudah viral dibandingkan klarifikasi.
Karena itu, literasi media publik menjadi agenda penting bagi masa depan jurnalisme Indonesia. Tanpa kesadaran kritis, masyarakat mudah terjebak dalam echo chamber algoritma media sosial yang memperkuat pandangan sempit, berpotensi menciptakan polarisasi, bahkan mengancam kohesi sosial.
Kesimpulan
Jurnalisme Indonesia kini berada di titik persimpangan. Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang menjangkau audiens luas secara instan. Namun di sisi lain, banjir informasi palsu dan dominasi platform global mengikis kepercayaan publik.
Masa depan media Indonesia hanya bisa bertahan jika jurnalis berpegang pada nilai inti: akurasi, integritas, dan keberpihakan pada kebenaran. Tantangan terbesar bukan lagi soal kecepatan, melainkan bagaimana menghadirkan jurnalisme yang relevan, berimbang, dan mampu memulihkan kepercayaan publik.
Kini dan esok, jurnalisme Indonesia dituntut tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi menjadi penuntun arah, pengawal demokrasi, dan penjaga akal sehat masyarakat.