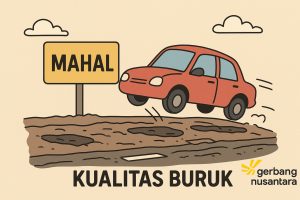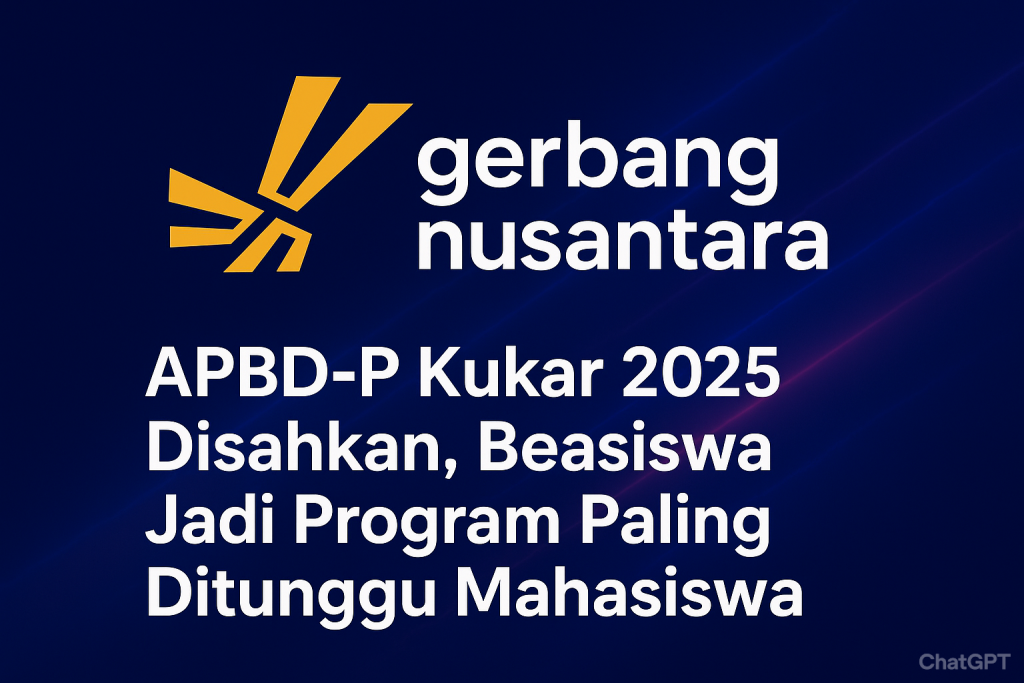Penulis: Suci Andriani, Mahasiswi Fisip Universitas Mulawarman
Samarinda –Rencana aksi mahasiswa pada 1 September lalu di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur menyisakan pertanyaan besar tentang nasib kebebasan berpendapat di Indonesia. Bukannya turun ke jalan menyuarakan aspirasi, 22 mahasiswa justru diamankan polisi sehari sebelumnya.
Penangkapan berlangsung di Kampus FKIP Universitas Mulawarman, Minggu (31/8) tengah malam. Dari hasil penggerebekan, aparat menyita 27 botol bom molotov, jeriken berisi bahan bakar, serta kain perca yang diduga disiapkan untuk unjuk rasa. Polisi menetapkan empat mahasiswa sebagai tersangka, sementara 18 lainnya dipulangkan usai pemeriksaan.
Namun, versi aparat ini menuai kritik. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda menilai proses hukum penuh kejanggalan. Mereka mempertanyakan transparansi asal-usul barang bukti serta menuding aparat melakukan kekerasan terhadap salah satu pengacara publik mereka yang mendokumentasikan aksi. Jaket robek, wajah lecet, hingga punggung memar menjadi bukti dugaan represif.
Di sisi lain, Wali Kota Samarinda Andi Harun justru mengapresiasi langkah cepat Polresta Samarinda. Ia menyebut keberhasilan aparat sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari ancaman keselamatan. Menurutnya, kasus ini harus dipisahkan antara tindak pidana dan penyampaian aspirasi. Kritik mahasiswa adalah hal wajar, namun tindakan yang berpotensi mengancam keamanan publik tidak bisa ditoleransi.
Pernyataan ini menegaskan bahwa secara konsep, aspirasi dan tindak pidana adalah dua hal berbeda. Namun, batas keduanya kerap kabur dalam praktik. Tanpa transparansi bukti dan proses hukum yang adil, tuduhan pidana bisa berubah menjadi legitimasi untuk membungkam kritik. Di titik inilah publik menaruh kecurigaan: apakah negara benar-benar menjaga keselamatan, atau justru menggunakan alasan keamanan untuk meredam suara mahasiswa?
Teori civil society dari Alexis de Tocqueville menekankan pentingnya ruang bebas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tanpa intervensi negara. Habermas melalui gagasan ruang publik menegaskan bahwa kebebasan berpendapat menjadi syarat lahirnya deliberasi rasional antara warga dan negara. Sementara itu, Antonio Gramsci melihat pembatasan suara masyarakat sipil sebagai bentuk hegemoni yang sengaja dipertahankan negara agar wacana alternatif tidak tumbuh.
Jika teori-teori itu disandingkan dengan kasus di Samarinda, terlihat jelas adanya kontradiksi. Negara menjanjikan kebebasan, tetapi pada saat yang sama masih mempraktikkan pembatasan. Mahasiswa, yang seharusnya berperan memperluas ruang demokrasi, justru berhadapan dengan risiko penangkapan.
Dalam perspektif Negara dan Masyarakat, kondisi ini mencerminkan relasi yang timpang. Negara kerap menempatkan dirinya sebagai pengendali penuh, sementara masyarakat sipil yang seharusnya bebas mengontrol kekuasaan justru dibatasi. Moral gerakan mahasiswa hadir sebagai benteng terakhir, mengingatkan bahwa kebebasan tidak boleh sekadar jargon, melainkan harus nyata dirasakan warga.
Kasus Samarinda akhirnya menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya soal janji di atas kertas. Hak bersuara yang dijamin konstitusi harus benar-benar hadir di ruang nyata, bukan sekadar slogan. Kini, bola ada di tangan negara: apakah memilih jalan transparansi dan perlindungan hak warga, atau terus mempertahankan pola represif yang hanya akan meruntuhkan kepercayaan publik.
Satu hal pasti, suara masyarakat sipil: termasuk mahasiswa, adalah denyut nadi demokrasi. Membungkam mereka sama saja dengan melemahkan demokrasi itu sendiri.