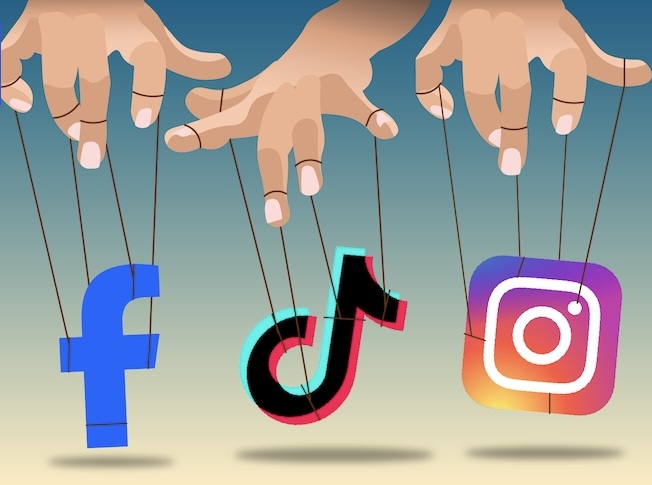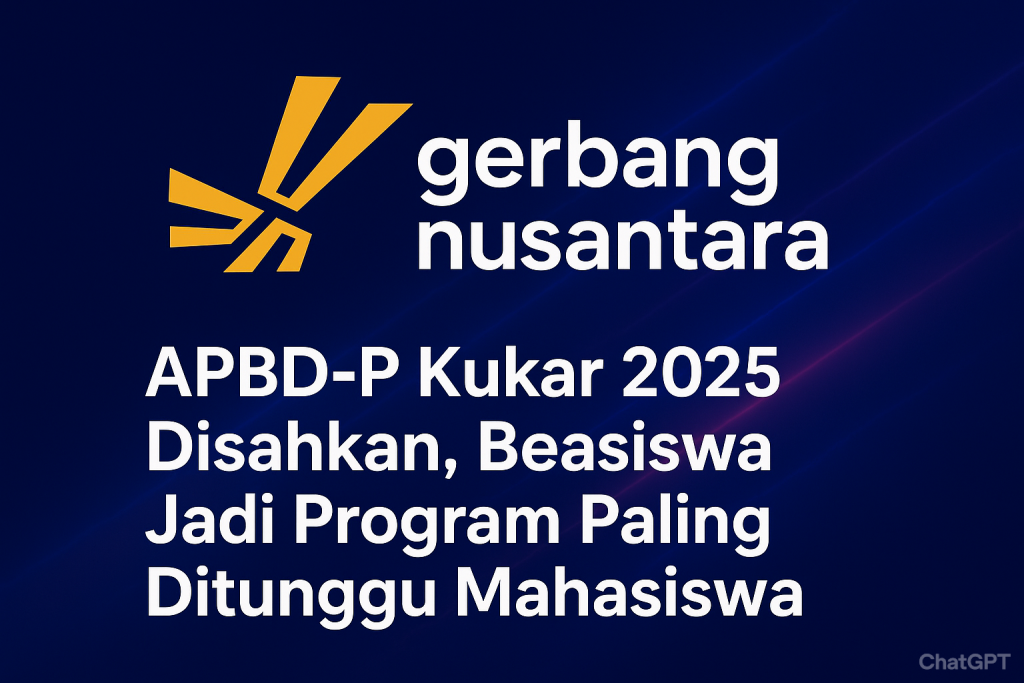Penulis: Muhammad Briyan Prama Irwansyah, Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta
Jakarta –Di tengah derasnya arus penyebaran informasi digital, “kebenaran” jurnalistik di Indonesia tengah diuji. Mulai dari maraknya disinformasi saat pemilu hingga ancaman hukum dan kekerasan terhadap pekerja media.
Data pemeriksa fakta menunjukkan lonjakan hoaks yang signifikan. Litbang MAFINDO mencatat, dalam setengah tahun 2024 ditemukan 2.119 hoaks—angka yang hampir menyamai total temuan sepanjang 2023. Fenomena ini menempatkan jurnalisme cek fakta sebagai garda terdepan dalam menjaga kebenaran publik.
Hasil survei Katadata Insight Center (2021) mengungkap bahwa 30–60 persen masyarakat Indonesia terpapar hoaks saat beraktivitas di internet. Lebih memprihatinkan lagi, hanya sekitar 21–36 persen yang sadar dan mampu mengenali bahwa informasi tersebut adalah hoaks.
“Yang lebih mengkhawatirkan lagi, dari sekian banyak yang terpapar, hanya sekitar 21% hingga 36% yang benar-benar sadar dan mampu mengenali bahwa informasi tersebut adalah hoaks,” ujar Alfons, Pemeriksa Fakta dari Tirto.id, dalam pemaparan materi di acara Jurnalistik Expo Day 2025 di Auditorium Perpustakaan PNJ, 29 September 2025.
Kondisi ini diperkuat oleh survei Tirto bersama Jakpat (2023), yang menunjukkan 37,87 persen orang Indonesia pernah secara tidak sengaja ikut menyebarkan informasi hoaks.
Faktor yang Melemahkan Jurnalisme
Beberapa faktor memperlemah proses verifikasi berita, antara lain tekanan ekonomi media lokal, derasnya arus konten tanpa verifikasi, serta regulasi multitafsir seperti revisi UU ITE yang kerap digunakan untuk mengkriminalisasi kritik dan membungkam kebebasan pers.
Kasus pencabutan sementara akses wartawan ke Istana karena pertanyaan kritis menggambarkan bagaimana otoritas dapat membatasi ruang kerja pers. Meski akses dipulihkan, peristiwa tersebut memicu keprihatinan akan perlindungan jurnalis.
Selain itu, fenomena clickbait journalism dan native advertising tanpa label “iklan” semakin memperburuk kaburnya batas antara berita dan promosi. Kehadiran teknologi kecerdasan buatan (AI) pun menambah kompleksitas. Dengan teknologi voice cloning dan synthetic video, konten palsu bisa dibuat seolah nyata sehingga masyarakat kesulitan membedakan fakta dari rekayasa.
Kebenaran yang Terkikis
Jika kebenaran jurnalistik terus dipertanyakan, masa depan jurnalisme Indonesia berisiko menghadapi tiga kemungkinan:
1. Normalisasi kebohongan digital – Masyarakat semakin terbiasa hidup dalam informasi palsu, dengan batas yang kabur antara berita dan opini.
2. Redaksi tanpa jurnalis – Otomatisasi media menggantikan reporter manusia, menghilangkan verifikasi moral dan empati sosial.
3. Ketakutan jurnalisme – Tekanan hukum dan politik membuat jurnalis memilih diam, menciptakan ruang kosong yang memberi kekuasaan tanpa koreksi.
Kini, kebenaran jurnalistik di Indonesia berada dalam ancaman ganda: manipulasi digital dan represi politik. Kecepatan informasi mengalahkan ketelitian, algoritma menggeser etika, dan hukum kerap menghantam para pelapor kebenaran.
Jika kondisi ini dibiarkan, masa depan jurnalisme bukan lagi tentang mencari kebenaran, melainkan mempertahankan keberanian untuk menyuarakannya.