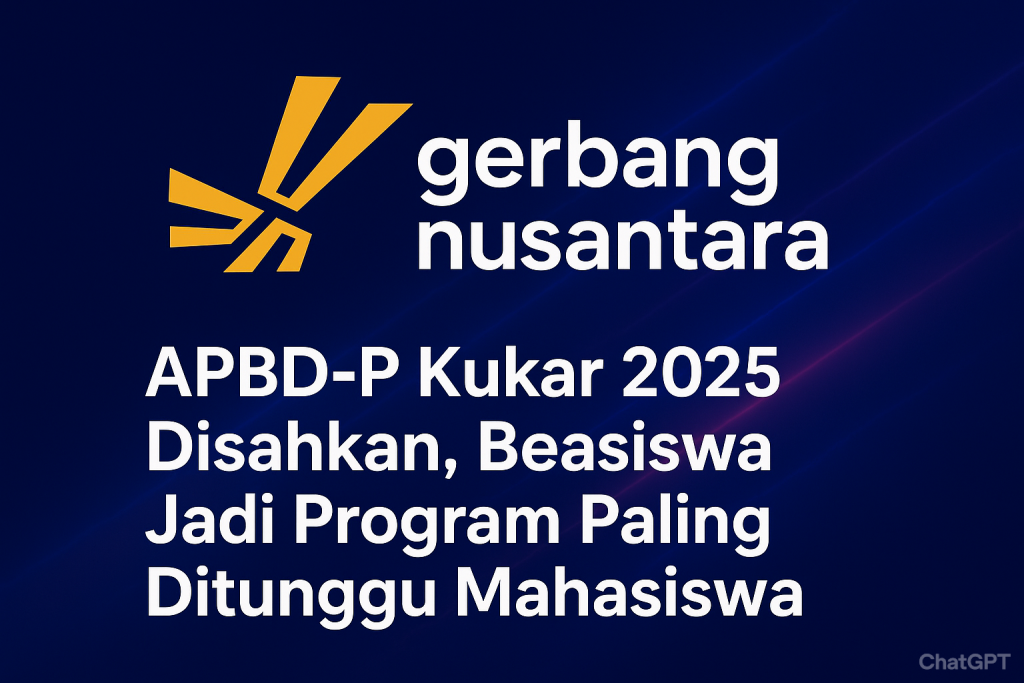Penulis: Rizal Nabiel Makarim, Mahasiswa Universitas Mulawarman
Setiap tahun, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) selalu menjadi sorotan publik. RAPBN bukan sekadar angka-angka yang tertulis dalam dokumen tebal, tetapi cermin arah kebijakan negara dalam setahun ke depan.
Pada RAPBN 2026, isu yang paling menonjol adalah bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara ambisi pembangunan, kebutuhan fiskal, dan tuntutan politik. Pertanyaannya: apakah politik anggaran dalam RAPBN 2026 benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat, atau justru lebih mengakomodasi kepentingan elite politik dan ekonomi?
Isu politik anggaran sangat relevan karena APBN adalah instrumen utama negara dalam mengatur distribusi sumber daya. Dalam konteks Indonesia pasca-2024, ketika pemerintahan baru mulai menegakkan arah kebijakannya, RAPBN 2026 akan menjadi momentum penting. Anggaran bisa menjadi alat strategis untuk mengurangi ketimpangan sosial, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat daya beli rakyat. Namun, ia juga bisa dipolitisasi: proyek pembangunan diarahkan ke daerah basis politik, anggaran subsidi dikurangi atas nama efisiensi, atau utang ditambah demi membiayai program yang lebih menguntungkan elite daripada rakyat.
Urgensi pembahasan RAPBN 2026 semakin tinggi karena beberapa alasan. Pertama, kondisi ekonomi global masih rentan akibat fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik. Kedua, Indonesia menghadapi tantangan struktural seperti ketergantungan pada utang luar negeri, rendahnya kualitas pendidikan, serta meningkatnya angka pengangguran muda.
Defisit APBN 2025 tercatat sebesar 2,45% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang menunjukkan masih tingginya beban pembiayaan negara. Di sisi lain, belanja subsidi energi pada tahun yang sama mencapai lebih dari Rp 300 triliun (Kemenkeu, Nota Keuangan 2025), angka yang sangat besar dan menyedot porsi signifikan dari belanja negara. Kondisi ini diperparah dengan rasio utang pemerintah yang per Juni 2025 berada di kisaran 39,1% PDB (DJPPR Kemenkeu), menandakan adanya ketergantungan yang cukup tinggi pada pembiayaan utang.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka per Februari 2025 masih mencapai 4,82% atau sekitar 7,2 juta orang (BPS). Hal ini mencerminkan tantangan besar di sektor ketenagakerjaan. Dengan gambaran tersebut, ruang fiskal 2026 menjadi sangat terbatas. Jika tidak dikelola secara hati-hati, RAPBN berisiko berubah menjadi jebakan utang jangka panjang alih-alih instrumen untuk mendorong kesejahteraan rakyat.
Dalam praktiknya, politik anggaran di Indonesia sering kali dikaitkan dengan “bagi-bagi kue pembangunan.” Infrastruktur masih mendominasi pos belanja, dengan anggaran lebih dari Rp 450 triliun pada tahun sebelumnya (APBN 2025). Infrastruktur memang penting, tetapi jika tidak diimbangi dengan belanja kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial, maka manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat bawah.
Di sisi lain, elite politik bisa memanfaatkan RAPBN untuk konsolidasi kekuasaan. Misalnya, proyek strategis nasional diarahkan ke daerah tertentu, atau anggaran kementerian lebih mengutamakan program pencitraan ketimbang program pemberdayaan. Pertanyaannya, apakah RAPBN 2026 berani memperbesar alokasi pada program-program yang langsung menyentuh rakyat—seperti perlindungan sosial, subsidi pangan, dan peningkatan kualitas pendidikan—atau tetap terjebak pada logika pembangunan fisik yang lebih menguntungkan kontraktor besar dan kelompok elite?
RAPBN 2026 adalah ujian awal bagi pemerintahan baru: apakah ia akan menjadikan anggaran negara sebagai instrumen kesejahteraan rakyat atau sekadar alat politik untuk menjaga kepentingan elite. Kesejahteraan rakyat seharusnya menjadi orientasi utama, bukan hanya jargon dalam pidato. Transparansi, akuntabilitas, dan keberanian memprioritaskan belanja sosial harus menjadi pijakan. Tanpa itu, RAPBN 2026 hanya akan menjadi dokumen politik yang mengulang siklus lama: rakyat menunggu, elite menikmati.