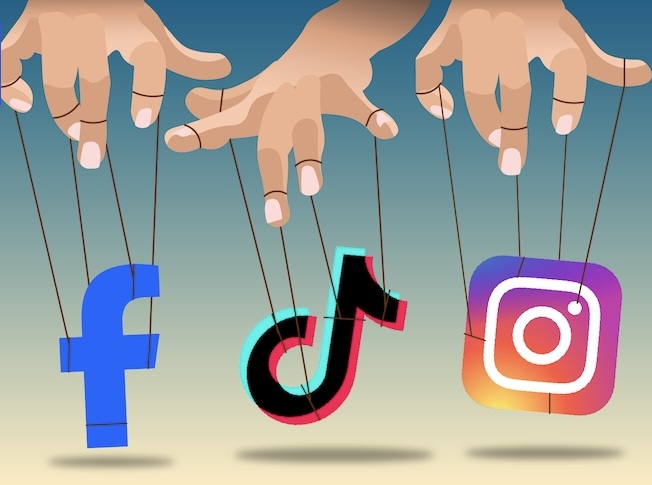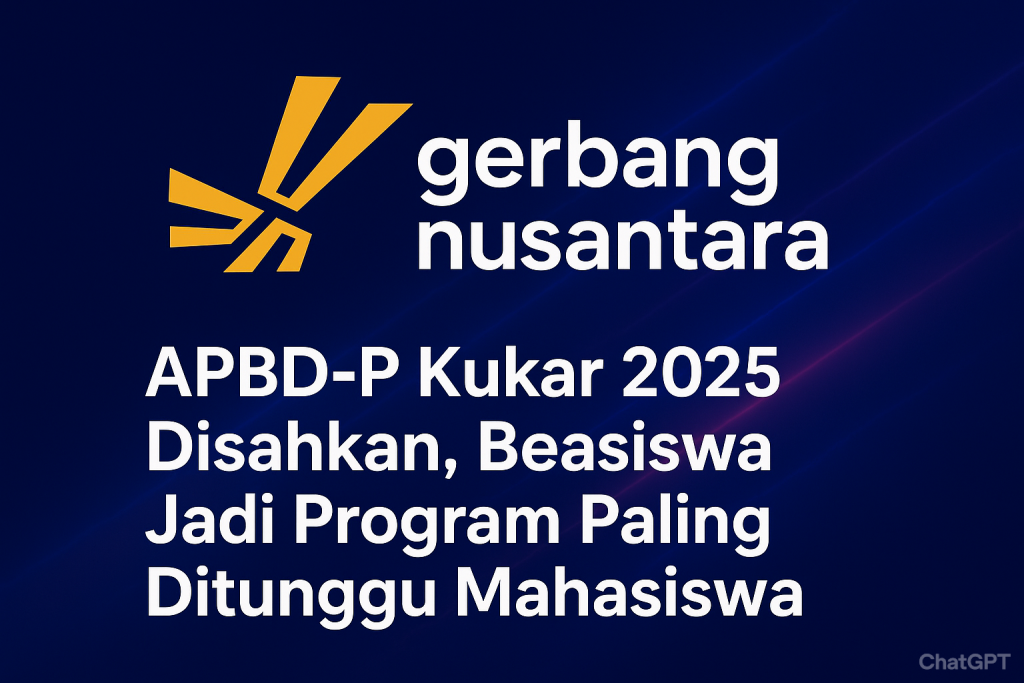Oleh: Laura Diandra Salzabilla, Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta
Masifnya pergerakan buzzer pasca Pemilu 2024 mengubah wajah ruang publik digital di Indonesia. Tidak hanya mengarahkan opini politik, mereka kini berperan besar dalam mengaburkan batas antara propaganda dan jurnalisme.
Setiap isu politik yang muncul di media sosial seperti X, TikTok, dan Instagram dengan cepat berubah menjadi medan tempur narasi yang dikuasai oleh pasukan buzzer. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat sekitar 92% kebisingan di ruang digital Indonesia berasal dari aktivitas buzzer.
Fenomena ini bukan sekadar perang opini, melainkan membentuk lanskap baru di mana publik sulit membedakan informasi yang diverifikasi dengan propaganda yang sengaja dirancang untuk mengarahkan persepsi.
Penelitian Propaganda Buzzer Politik pada Pemilihan Presiden 2024 (Husein, 2024) menemukan bahwa jaringan buzzer menggunakan konten visual dan bahasa emosional untuk membangun kedekatan dengan pemilih muda, sekaligus melemahkan kepercayaan terhadap media arus utama.
Husein juga menegaskan, buzzer kini bukan lagi sekadar alat kampanye, melainkan pabrik narasi yang menentukan apa yang dianggap benar dan salah. Dalam situasi ini, media massa yang selama ini menjadi penentu kebenaran publik justru dipaksa beradaptasi agar tidak tertinggal oleh kecepatan algoritma.
“Gemoy” dan Bias Pemberitaan
Kampanye politik 2024 menjadi titik balik profesionalisasi jaringan buzzer. Mereka bekerja secara terstruktur layaknya agensi komunikasi politik dengan tim konten, analis data, hingga pengendali narasi.
Salah satu contohnya adalah kampanye citra “Prabowo Gemoy” yang viral di berbagai platform media sosial. Menurut riset Fenomena Buzzer Politik Prabowo di Media Sosial dan Dampaknya terhadap Legitimasi Media Pers (Apriyanto, 2025), narasi ini sukses membentuk citra politik yang ramah dan lucu, sekaligus menutupi isu-isu kontroversial.
Strategi tersebut efektif karena menyentuh sisi emosional generasi muda, bukan pada rasionalitas politik. Di sisi lain, media arus utama menghadapi dilema. Beberapa redaksi mengakui adanya tekanan internal untuk menyesuaikan diri dengan tren buzzer demi menjaga trafik pembaca.
Situasi ini menciptakan “krisis kecepatan”, di mana jurnalis dipaksa berlomba dengan algoritma. Ketika verifikasi fakta memakan waktu, narasi buzzer sudah lebih dulu membentuk persepsi publik yang mengakar. Akibatnya, fakta perlahan tak berdaya.
Kebenaran Akan Semakin “Relatif”
Pergerakan buzzer yang masif pasca Pemilu 2024 menunjukkan arah yang mengkhawatirkan. Dalam lima tahun ke depan, pengamat memperkirakan tiga pola besar yang akan menguat:
1. Profesionalisasi jaringan buzzer akan semakin menjamur, bekerja layaknya konsultan politik digital dengan anggaran khusus, pendekatan data analytics, serta konten otomatis berbasis AI.
2. Saturasi algoritmik membuat publik lebih sering terekspos pada informasi emosional ketimbang berita faktual. Teknologi seperti deepfake, bot otomatis, dan konten berulang akan memperbanyak kebenaran alternatif yang sulit diverifikasi.
3. Krisis kepercayaan terhadap media akan semakin parah jika redaksi tidak memperkuat transparansi dan independensi. Masyarakat cenderung mencari informasi sesuai pandangan pribadi, bukan dari media kredibel. Hal ini berpotensi membentuk gelembung kebenaran yang saling bertabrakan di ruang digital.
Meski demikian, masih ada harapan. Inisiatif seperti CekFakta.com, Project Multatuli, dan berbagai kolaborasi lintas media berupaya mengembalikan makna jurnalisme sebagai kerja pengetahuan, bukan sekadar reaksi terhadap tren algoritma.
Kebenaran Terancam Dijual
Namun, derasnya arus buzzer telah mengaburkan batas antara jurnalisme, hiburan, dan propaganda. Saat narasi viral lebih dipercaya daripada fakta terverifikasi, demokrasi kehilangan fondasinya.
Jika media tidak segera beradaptasi, kebenaran berisiko menjadi komoditas yang dijual kepada pihak yang mampu membeli suara terbanyak. Publik perlahan akan kehilangan arah pada kenyataan.
Media tak lagi menjadi penunjuk jalan, dan kebenaran berubah menjadi gema yang direkayasa. Di tengah kekacauan itu, orkestrasi suara yang menyerupai fakta akan terus dimainkan merdu, menipu, dan nyaris tak terbantahkan.